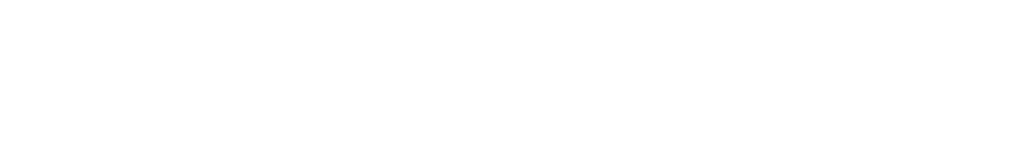Soalan
Assalamualaikum ustaz. Antara puasa enam dan berbuka jika dijemput ke jamuan raya, manakah yang lebih afdhal?
Jawapan
Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikut jejak langkah Baginda hingga ke Hari Kesudahan.
Pada asasnya, seseorang yang melakukan puasa sunat, kemudian dia berbuka dengan sengaja, maka hukumnya adalah makruh. Namun, dia tidak diwajibkan untuk mengqadha’ puasa tersebut.[1]
Ibn Rusyd menyebut: “Ulama’ bersepakat berkenaan hukum membatalkan puasa sunat, bahawa tidak ada kewajiban qadha’ bagi seseorang yang membatalkan puasa sunatnya kerana adanya uzur tertentu. Namun para ulama’ berbeza pendapat tentang seseorang yang membatalkan puasa sunatnya dengan sengaja atau tanpa adanya uzur tertentu. Jika menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka mewajibkan untuk qadha’ puasa sunat tersebut. Namun, tidak wajib mengqadha’ puasa sunat yang dibatalkan jika menurut pendapat Imam al-Syafi’i dan sebahagian ulama’ yang lain[2]
Antara dalil bahawa dibolehkan untuk membatalkan puasa sunat ialah, seperti dalam hadith yang diriwayatkan daripada Ummu Hani’ R.Anha, bahawa Nabi SAW bersabda:
الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
Maksudnya: “Seseorang yang berpuasa sunat menjadi penentu dirinya. Jika dia mahu dia boleh teruskan berpuasa, dan jika mahu dia juga boleh berbuka.”[3]
Berbalik kepada persoalan di atas, dibenarkan bagi orang yang melakukan puasa sunat untuk berbuka apabila dijemput ke sesuatu majlis jamuan. Hal ini berdasarkan hadith daripada Abu Sa’id al-Khudri R.A, katanya:
دَعَا رَجُلٌ إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاكُمْ أَخَاكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ
Maksudnya: “Seorang sahabat telah menjemput ke jamuan makan. (Setelah dihidangkan makanan), salah seorang daripada sahabat berkata: “Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Lalu Rasullullah SAW bersabda: Saudara kamu telah menjemput dan bersusah payah untuk kamu. Berbukalah dan gantilah pada hari yang lain sekiranya kamu mahu.”[4]
Menurut ulama’ Syafi’i dan Hanabilah, dalam situasi seseorang yang dijemput ke majlis makan dalam keadaan seseorang itu berpuasa sunat, maka mereka berpendapat bahawa sunat berbuka sekiranya membebankan dan menyusahkan tuan rumah. Hal ini kerana dibenarkan baginya untuk menggantikan puasa sunat itu pada hari yang lain. Di samping itu, ia juga dapat memberi kegembiraan kepada pihak tuan rumah yang menjemputnya. Akan tetapi, jika keadaan dia terus berpuasa itu tidak memberatkan tuan rumah, maka afdhal baginya untuk meneruskan puasa tersebut tanpa perlu membatalkannya.[5]
Al-Khatib al-Syirbini berkata: “Sekiranya (dalam membatalkan puasa tersebut) ada uzur, seperti menemani tetamu makan jika dia tersinggung apabila tuan rumah tidak makan atau sebaliknya, maka tidak makruh, bahkan dianjurkan untuk membatalkan puasa. Adapun jika tidak tersinggung apabila salah seorangnya menolak untuk makan, maka lebih utama untuk tidak membatalkan puasa sunat, sebagaimana disebut dalam kitab al-Majmu’.”[6]
Syeikh Taqiyuddin Abu Bakar al-Hisni menyebut: Orang yang sedang berpuasa sunat tidak wajib menyelesaikannya sehingga waktu berbuka, yakni Maghrib. Namun alangkah baiknya untuk diselesaikan sehingga waktu berbuka. Tidak ada kewajiban qadha’ baginya jika dia membatalkan puasa sunat di pertengahan jalan. Tetapi sunat baginya mengqadha’ puasanya. Adakah hukumnya makruh jika dia membatalkan puasa sunat itu? Masalah ini perlu dipertimbangkan. Sekiranya dia membatalkannya dengan sebab adanya keuzuran, maka tidak makruh. Namun, jika sebaliknya, yakni tidak disebabkan adanya uzur tertentu, maka perbuatan membatalkan puasa sunat itu adalah makruh.[7]
Salah satu bentuk uzur syar’i adalah apabila ingin memuliakan dan menghormati tuan rumah yang menjemput dan menjamu makan bagi orang berpuasa yang berkunjung ke rumahnya.
Syeikh Taqiyuddin al-Hisni berkata: “Salah satu bentuk uzur syar’i adalah untuk memuliakan orang yang menjemput dan menjamunya dalam keadaan dia tertegah daripada makan.[8]
Syeikh Zainuddin al-Malibari dalam kitab Fath al-Mu’in[9] berkata: Disunatkan makan (ketika bertamu) dalam keadaan dia sedang berpuasa sunat, walaupun sunat muakkad. Ini bagi menyenangkan hati tuan rumah, sekiranya mempertahankan untuk berpuasa akan memberatkan bagi tuan rumah. Hal ini meskipun dia sudah berada di akhir waktu siang kerana adanya perintah untuk berbuka. Dia akan diberi pahala atas puasa yang telah luput dan sunat menggantinya pada hari yang lain. Namun, sekiranya dengan mempertahankan untuk berpuasa itu tidak memberatkan bagi tuan rumah, maka tidak disunatkan berbuka, malah lebih utama untuk mempertahan dan meneruskan puasanya.
Justeru, seseorang boleh memilih untuk membatalkan puasa sunatnya apabila dia diundang ke jamuan makan. Dengan itu, ia dapat menyenangkan hati tuan rumah yang menjemputnya itu. Daripada Ibn ‘Umar R.Anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda:
أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ , وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ , أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً , أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا , أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا , وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا
Maksudnya: “Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuatkan Muslim yang lain bahagia, menghilangkan kesusahan daripada orang lain, melangsaikan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku yang Muslim untuk satu keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini – masjid Nabawi – selama sebulan penuh.”[10]
Menurut Imam al-Nawawi, jika orang yang menjemput berasa tidak suka jika orang yang dijemput itu tetap berpuasa, maka hendaklah dia membatalkan puasanya. Sekiranya tidak timbul perasaan seperti itu, maka tidak mengapa untuk tidak membatalkan puasanya.[11]
Pengarang kitab Fatawa al-Kubra[12] menyebut: “Pendapat yang paling baik dalam masalah ini, jika seseorang yang menghadiri walimah (undangan makan) dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka sekiranya ia menyakiti hati tuan rumah yang menjemput kerana enggan untuk makan, maka lebih utama ketika itu untuk makan. Namun, jika tidak sampai menyakiti hatinya, maka meneruskan puasa lebih baik. Akan tetapi, tidak sewajarnya bagi tuan rumah untuk memaksa yang dijemput itu untuk makan jika dia enggan untuk makan. Kerana kedua-dua keadaan yang disebutkan tadi sama-sama boleh. Memaksa pada hal yang sebenarnya bukan wajib adalah merupakan sebahagian daripada pemaksaan yang dilarang.[13]
Selain itu, orang yang memilih untuk berbuka apabila dijemput untuk ke jamuan makan juga akan lebih dapat menjaga keikhlasan dalam amalan.
Ma’ruf al-Karkhi yang terkenal dengan kezuhudannya pernah ditanya, “Bagaimana engkau berpuasa?” Beliau tidak terus menjawab, sebaliknya berpusing-pusing dalam jawapannya dengan berkata, “Puasa Nabi kita SAW seperti ini dan seperti itu. Puasa Daud seperti ini dan seperti itu.” Orang yang bertanya terus mendesak agar Ma’ruf memberikan jawapan. Ma’ruf kemudian berkata, “Di pagi hari, aku berpuasa. Jika ada yang mengundangku untuk makan, maka aku makan. Aku tidak mahu mengatakan bahawa aku sedang berpuasa.”[14]
Di samping itu, Rasulullah SAW juga mengajar supaya berdoa apabila seseorang itu berpuasa, kemudian dia dijemput untuk menghadiri majlis jamuan. Abu Hurairah R.A meriwayatkan dalam sebuah hadith, bahawa Rasulullah SAW bersabda:
إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ
Maksudnya: “Jika salah seorang di antara kamu diundang makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika dalam keadaan berpuasa, maka doakanlah orang yang mengundangmu. Jika dalam keadaan tidak berpuasa, maka santaplah makanannya.”[15]
Menurut Imam al-Nawawi, terdapat perbezaan pandangan ulama’ berkenaan ungkapan ‘فَلْيُصَلِّ’ dalam hadith di atas. Sebahagian ulama’ berpendapat, makna perkataan ‘solat’ dalam hadith ini adalah mengerjakan ibadah solat dengan rukuk dan sujud. Ertinya, dia mengerjakan solat di rumah orang yang mengundang, sehingga dia mendapat keutamaan solat dan pengundang serta yang hadir mendapat keberkatan. Manakala majoriti ulama’ berpendapat bahawa makna ‘solat’ dalam hadis di atas adalah mendoakan orang yang mengundang dengan doa keampunan atau keberkatan, atau seumpamanya. Dan makna lafaz ‘solat’ pada bahasa adalah doa.[16]
Kesimpulan
Berdasarkan nas dan keterangan di atas, kami nyatakan bahawa jika orang yang mengundang tidak tersinggung dan memahami, maka dia boleh meneruskan puasanya di samping mendoakan kepada orang yang mengundang tersebut dengan kebaikan dan keberkatan atas majlis tersebut.
Sebaliknya, jika dalam keadaan pihak yang mengundang itu merasa tersinggung atau keberatan, dan dikhuatiri dengan tempahan yang dilakukan akan menyebabkan berlakunya pembaziran, maka dalam keadaan ini, lebih afdhal baginya untuk membatalkan puasa agar lebih dapat menjaga perasaan dan hubungan silaturrahim.
Wallahu a’lam.

Bertarikh: 18 Mei 2022 bersamaan 17 Syawal 1443H
[give_form id=”14962″]
[1] Lihat al-Fiqh al-Manhaji, 2/118
[2] Lihat Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, 1/287
[3] Riwayat al-Tirmizi (32)
[4] Riwayat al-Tabarani dalam al-Mu’jam al-Ausat (3/306). Al-‘Ajluni dalam Kasyf al-Khafa’ (1/238) menilai hadis ini sebagai dha’if. Manakala dalam hadis ini dinilai sebagai hasan dalam kitab Irwa’ al-Ghalil (1952).
[5] Lihat al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 45/118
[6] Lihat Mughni al-Muhtaj, 1/448
[7] Lihat Kifayah al-Akhyar, 1/296
[8] Lihat Kifayah al-Akhyar, 1/296
[9] hlm. 176
[10] Riwayat al-Tabarani dalam al-Mu’jam al-Kabir (13280). Hadis ini dinilai hasan seperti dalam kitab Sahih al-Jami’ (176).
[11] Lihat Syarh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim, 9/210
[12] 5/477
[13] Lihat Fatawa al-Kubra, 5/477
[14] Lihat Siyar A’lam al-Nubala’, 9/341
[15] Riwayat Muslim (1431)
[16] Lihat Syarh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim, 9/236